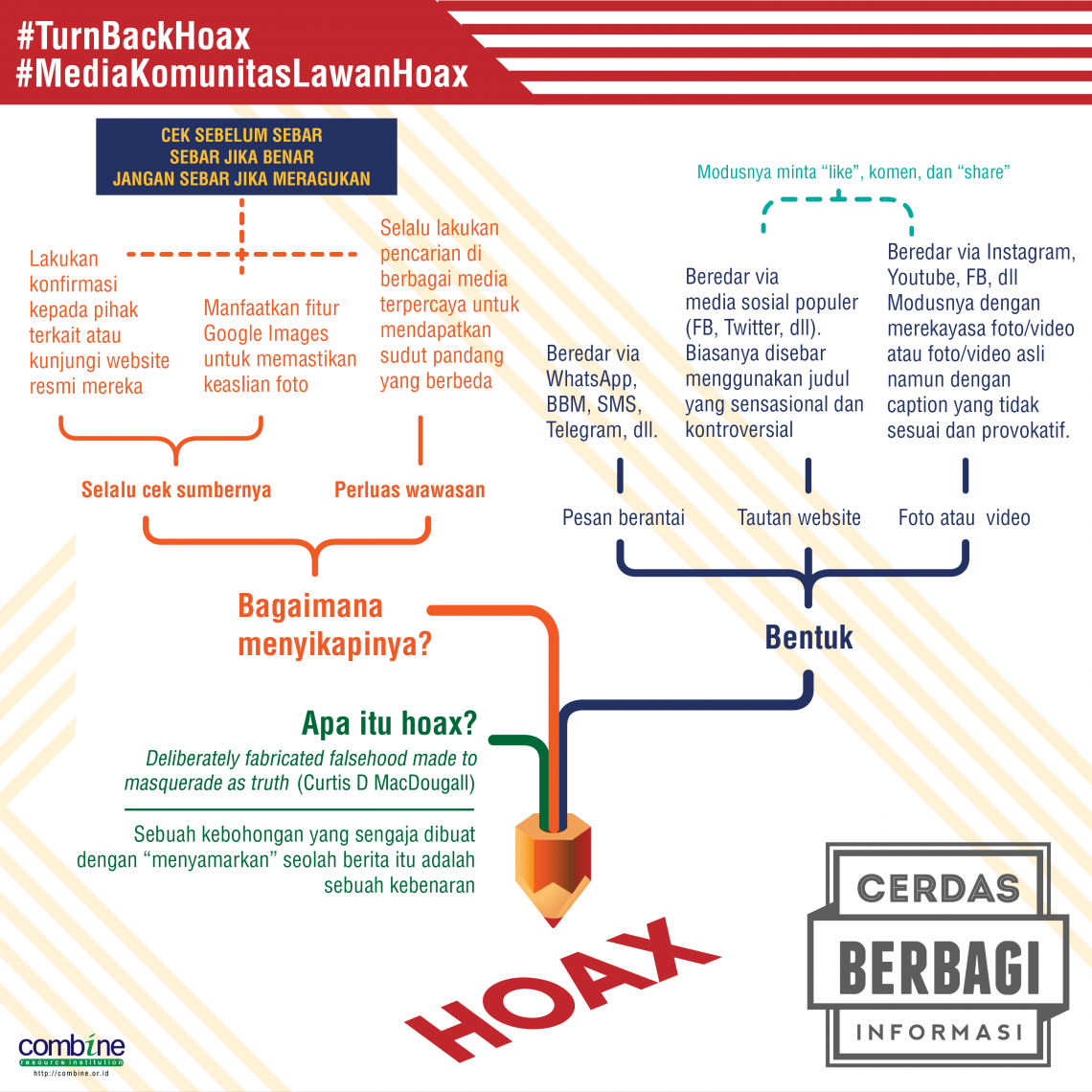Oleh: Wisnu Prasetya Utomo
Peneliti media Remotivi
Bagaimana mengatasi berita-berita palsu (hoaks) yang semakin hari semakin membanjiri dan menembus ruang-ruang personal kita?
Bagi sebagian orang, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan melakukan periksa fakta (fact checking), fenomena yang berkembang di berbagai negara seiring dengan perkembangan hoaks itu sendiri. Asumsinya, dengan melakukan periksa fakta, informasi-informasi yang terbukti bohong bisa dipatahkan dengan sendirinya. Orang yang awalnya membaca informasi palsu kemudian akan disadarkan setelah membaca informasi yang sebenarnya.

Namun, kenyataannya memberantas informasi hoaks tidak semudah itu. Usaha untuk menampilkan fakta yang sebenarnya kerap kali berakhir dengan sia-sia. Ini terjadi karena pada dasarnya problem utama tidak terletak pada informasi palsu itu sendiri, melainkan pada apa yang diyakini oleh seseorang. Keyakinan dengan dasar apapun–seperti politik, agama, kultur– kerap membuat orang mengedepankan prasangka alih-alih fakta.
Prasangka tersebut yang kerap kali dibawa ketika berpendapat di ruang publik seperti di media sosial. Tak terkecuali ketika membaca dan membagi informasi. Dalam kondisi demikian, kebenaran informasi—apakah ia berbasis pada fakta atau kebohongan–menjadi tidak penting lagi. Hal yang dianggap lebih penting adalah, apakah informasi tersebut mengafirmasi keyakinan yang dimiliki atau tidak.
Informasi yang faktual dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan cenderung akan diabaikan kalau tidak sesuai dengan keyakinan. Sebaliknya, setidak masuk akal apapun sebuah informasi palsu, ia akan dipercaya sebagai sebuah kebenaran jika berada garis keyakinan yang sama dengan pengakses informasi. Fenomena Ini menjelaskan mengapa bahkan orang yang intelek sekalipun bisa dengan mudah percaya informasi palsu. Dengan kata lain, informasi-informasi palsu ibarat bensin yang disiramkan ke api.
Pada titik ini, relevan untuk mendiskusikan literasi media sebagai salah satu upaya untuk melawan banjir informasi palsu yang pelan-pelan merusak kehidupan demokrasi kita. Perlu dicatat, sebagai salah satu upaya, tentu ia masih membutuhkan faktor-faktor lain jika ingin menekan bahkan memberantas informasi palsu. Artikel pendek ini tidak akan membahas faktor-faktor lain tersebut dan hanya membatasi pada literasi media.
Literasi media sendiri tidak sekadar kemampuan untuk membedakan mana informasi yang benar dan bohong. Lebih dari itu, literasi media memberi perhatian pada kemampuan berpikir kritis dalam membaca pesan-pesan media atau informasi. Dalam konteks ini, ia menjadi perangkat pengetahuan yang membuat orang bisa membaca sebuah informasi between the lines (mengambil kesimpulan-red).
Sebagai contoh, dalam membaca informasi sebuah media kita tidak bisa menelan mentah-mentah begitu saja. Literasi media memungkinkan upaya pembacaan atas sebuah berita menjadi lebih jauh dari apa yang tampak dalam teks berita. Sebuah berita media adalah produk dari berbagai kontestasi kepentingan. Setiap media digerakkan oleh kepentingan ekonomi politik masing-masing. Begitu pula dengan informasi palsu yang beredar di media sosial. Ia digerakkan oleh “tangan-tangan tak terlihat” yang punya kepentingan tertentu dengan menyebarkan informasi palsu.
Kita bisa melihat dari pengalaman Amerika Serikat dan Inggris di tahun 2016. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat diwarnai ledakan informasi palsu dalam periode pemilihan umum. Ledakan yang sedikit banyak memiliki peran dalam terpilihnya Trump. Sementara di Inggris, referendum yang memutuskan negara tersebut keluar dari Uni Eropa juga diwarnai dengan informasi palsu yang membuat banyak warga memilih tanpa basis fakta dan data yang memadai. Keputusannya lebih didorong dan digerakkan oleh prasangka sebagai konsekuensi dari gempuran informasi-informasi palsu.
Melihat dua kasus tersebut, tak mengherankan jika kamus Oxford menjadikan kata post-truth sebagai word of the year pada 2016. Post-truth adalah kondisi dimana fakta tidak lagi menjadi penting dan prasangka menjadi bahan pertimbangan yang paling utama dalam mengambil sebuah keputusan tertentu. Dalam konteks di Indonesia, kita bisa melihat fenomena ini dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Potensi semakin mewabahnya informasi palsu dan mempengaruhi pilihan politik warga akan semakin membesar di tahun-tahun ke depan.
Karena itu, bahasan literasi media tetap penting. Selama ini, sebagai sebuah wacana, literasi media lamat-lamat terdengar, khususnya bila dibandingkan dengan upaya-upaya lain dalam menghadapi gelombang informasi palsu dan problem berita-berita media lainnya. Misalnya saja seperti upaya Dewan Pers memverifikasi media-media arus utama yang salah satu alasannya adalah meminimalisir penyebaran informasi palsu. Atau juga model pemblokiran situs-situs seperti yang biasa dilakukan pemerintah.
Membangun generasi kritis literasi media
Literasi media jarang terdengar karena efeknya baru bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Sebabnya, dalam literasi media yang dibangun adalah sebuah cara berpikir yang tentu membutuhkan proses panjang. Bahasan tentang literasi media sebenarnya sudah lama muncul. Tapi sifatnya masih parsial dan sulit menyentuh substansi persoalan. Hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang melakukan ini seperti kampus dan organisasi masyarakat sipil dengan sifatnya yang masih elitis dan gagal menjangkau masyarakat luas.
Karena itu, saya berpendapat bahwa dalam jangka panjang, literasi media harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Gagasan ini tidak berlebihan. Survei yang dilakukan Nielsen (2016) menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia didominasi oleh generasi Z (usia 10 -19 tahun) dan generasi millenniall (usia 20-34 tahun) dengan masing-masing sebesar 34% dan 48%. Ini artinya para pengakses internet baik yang menggunakannya untuk mengakses media daring maupun media sosial kebanyakan adalah pelajar.
Ini adalah tantangan literasi media di era digital. Generasi Z dan millennial adalah generasi yang tumbuh besar bersama perangkat teknologi dan internet. Sebagai digital natives (generasi yang lahir di saat era digital sudah berlangsung dan berkembang pesat-red), mereka menerima media sosial sebagai sesuatu yang taken for granted (sesuatu yang sudah biasa-red). Ini berbeda dengan generasi orang tua mereka yang masuk dalam kategori digital immigrant (generasi yang lahir sebelum generasi digital belum begitu berkembang-red).
Melihat fakta tersebut, tentu relevan untuk memasukkan literasi media ke dalam kurikulum pendidikan dan menjadi bagian dari pelajaran yang mereka terima secara formal. Bukan hanya berdasarkan pada kepekaan masing-masing individu semata. Dengan begitu, sejak masih belajar di sekolah, para pelajar dibekali perangkat pengetahuan yang penting bagi mereka khususnya dalam mengakses informasi di internet.
Dengan kata lain, fokus literasi media dalam kurikulum pendidikan adalah memastikan anak-anak mampu membaca perkembangan teknologi termasuk konsekuensi pesan di dalamnya secara kritis. Serta yang lebih penting adalah menggunakannya secara bijak. Tidak hanya berkaitan dengan konflik sosial, hal ini penting sebagai upaya juga menangkal gejala radikalisi agama yang marak menggunakan medium media sosial.

Sementara itu dalam jangka pendek, yang dibutuhkan adalah peran dari para pemangku kepentingan baik itu regulator media, pemerintah, dan yang lebih penting adalah kelompok masyarakat sipil khususnya komunitas-komunitas yang bersentuhan langsung dengan warga yang terpapar informasi palsu. Dalam masyarakat yang rentan terpapar informasi palsu, kebutuhan akan literasi media menjadi begitu mendesak. Bagaimana caranya?
Seperti disinggung di atas, pada dasarnya literasi media berkaitan dengan kesadaran kritis. Karena itu, untuk menumbuhkannya adalah dengan tetap menumbuhkan skeptisisme pada berbagai informasi yang datang. Baik itu dari media-media arus utama, apalagi dari sumber yang tidak bisa diverifikasi. Kita tidak boleh memberikan kepercayaan seratus persen kepada media arus utama dan sumber-sumber lainnya. Sebaliknya, tidak boleh juga berlebihan dalam meragukan sebuah informasi kalau memang ia bisa diuji dan dipertanggungjawabkan.
Berangkat dari ketidakpercayaan tersebut, yang dilanjutkan pada tahap selanjutnya adalah melakukan upaya pembacaan terhadap sebuah informasi atau berita dengan lebih menyeluruh. Ini melampaui benar atau salah. Misalnya dengan menghubungkan sebuah berita media dengan kepemilikan media atau kepentingan ekonomi politik. Atau juga menautkan antara informasi palsu dengan siapa-siapa saja yang secara aktif menyebarkannya.
Upaya ini tentu saja berada dalam wilayah ideal, dan patut dicatat bahwa literasi media bukanlah sebuah panasea (obat-red) yang bisa dengan tiba-tiba menghilangkan rasa sakit. Ia menjadi upaya terus-menerus yang hasilnya kerap tidak datang dalam waktu singkat. Apalagi seperti di era digital saat ini yang penuh dengan disrupsi (tercerabut dari akarnya-red). Tetapi waktu sudah mendesak, jika ia tidak dilakukan, kita semua akan dengan mudah tersapu gelombang informasi palsu, sampai jauh.